Oleh: Intan Rahadyanti
Saya masih ingat, waktu itu tahun 1985. Seorang perempuan berparas manis, tanpa riasan di wajahnya, memasuki sebuah supermarket di kawasan Depok, Semarang. Penampilannya terlihat beda. Membawa keranjang belanja, ia memakai atasan lengan panjang lurik, seperti Surjan dan celana panjang hitam membungkus tubuhnya yg padat. Rambutnya digulung seadanya. Ia memakai sandal dengan hak.
Saya yang waktu itu menjadi SPG sebuah produk makanan kecil, beberapa kali melihat kedatangannya. Yang menarik lagi, ia hanya selalu membeli permen. Banyak permen. Saya tidak pernah melihatnya berbelanja barang lain. Saya tidak tahu siapa dia. Saya hanya mengira wanita itu istimewa. “Itu NH Dini. Yang pengarang ‘Pada Sebuah Kapal'” bisik seorang teman yang juga SPG, tetangga NH Dini.
Belakangan saya tahu, bahwa saat itu Dini sedang mengambil langkah besar. Berpisah dari suami nya, seorang diplomat Perancis, dan meninggalkan dua anak remajanya, kembali ke tanah kelahirannya, Indonesia, dan kembali bermukim di rumah tempat ia dilahirkan di Kampng Sekayu, Semarang.
Seperti selembar kain yang dihiasi bordir cantik dengan motif yang rumit, itulah perasaan saya ketika pertama kali menelusuri lembar demi lembar ‘ Pada Sebuah Kapal’. Saya, yang waktu itu terbiasa membaca novel renyah ala ‘Ali Topan Anak Jalanan’, terhenyak, mencoba melumat kata dan makna dari tulisan Dini. Rangkaian katanya tidaklah sederhana, tapi saya tidak bisa berhenti menikmati keindahannya.
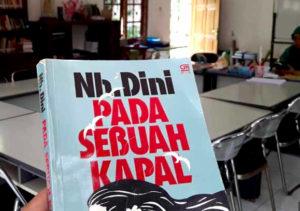
Tak bisa dimungkiri, ‘Pada Sebuah Kapal’ berisi kisah panjang perjalanan hidup seorang NH Dini yang di novel nya diperankan oleh tokoh bernama Sri. Ia sendiri tak menampik meskipun juga tak mengakui, ketika seorang jurnalis menanyakan hal tersebut. Menurut Dini, sudah lazim seorang penulis menuangkan pengalaman pribadi dalam karya nya.
Di novel itu, Dini berkisah dengan haru, ketika suatu hari sepulang sekolah, mendapati rumah nya dipenuhi tetangga. Dengan masih memegangi sepedanya, ia menerima kabar, bahwa ayahanda nya telah berpulang. Setelah itu, adalah kisah tentang masa remaja nya dibesarkan di keluarga sederhana dengan orang tua tunggal. Namun, sang ibu memberi ruang seluas-luasnya kepada Dini remaja untuk menjelajah bakatnya. Ia pun aktif mengisi acara di RRI Semarang. Membaca puisi, menulis naskah sandiwara radio. Yang semuanya menjadi tunas-tunas dari bakat menulisnya.
Dini juga berkisah tentang tragedi lain dalam hidup Sri, ketika tunangannya, seorang penerbang AU gugur ketika berlatih. Ia larut dalam kegalauan, karena saat itu ia dan tunangannya sudah melewati batas hubungan yang seharusnya. Hal itulah yang membuat Sri menjatuhkan pilihan pada pria asing. Di novel itu bernama Charles, seorang diplomat Perancis. Persis sama dengan kehidupan nyata Dini.
***
Suasana pagi itu di Aula Santa Anna, terasa hening. Saya duduk di antara puluhan pelayat yang terdiri dari sesama penghuni Wisma Lansia Harapan Asri, di mana sastrawati besar ini menghabiskan tahun-tahun terakhir hidupnya. Nampak pula beberapa seniman lokal, rombongan kecil anak sekolah didampingi gurunya, para kerabat dan yang menarik, para pegawai toko buku Gramedia yang terlihat datang silih berganti.
Prosesi hari itu, dimulai dengan shalat jenazah yang dilakukan sekelompok bapak-bapak. Setelah itu, para sahabat bergantian memberikan sambutan, kenangan masing-masing tentang almarhumah NH Dini. Yang paling membuat hati trenyuh adalah sambutan ibu Sulis Bambang, sahabat lama dan tokoh seniman Semarang.
Dengan suara lembut dan tersendat, Bu Sulis menceritakan bagaimana sahabatnya tersebut harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, karena royalti yang didapat dari bukunya tidak sepadan nilainya. Bu Sulis juga mengenang, bagaimana teman teman NH Dini banyak membantu nya dalam mengatasi kesulitan keuangan nya. Dalam beberapa kesempatan, Dini sering memuji Goenawan Mohamad yang selalu membantu mengirimi uang. ”Dik Goen yang baik itulah yang selalu memberikan bantuan,” kata Dini kepada seorang sahabatnya.

Rasanya masih tak percaya bahwa hanya beberapa meter di depan saya, di dalam sebuah peti berukir terbaring jasad salah satu seniwati besar Indonesia. Usianya memang sudah lanjut, 82 tahun. NH Dini yang terlahir dengan nama Nurhayati Srihardini Siti Nukatin itu, juga didera beberapa penyakit yang membuat nya harus menjalani terapi tusuk jarum seminggu sekali di kawasan Pecinan, Semarang. Namun, ia masih terlihat bugar dan cantik untuk ukuran perempuan seusianya.
Tak ingin mempertanyakan Takdir Tuhan, tapi ada kesedihan yang tidak berhenti melintas, mengingat bagaimana tragedi kembali menghampiri nya, menjadi penutup hidup nya. Sebuah truk yang patah as rodanya, berjalan mundur tak terkendali, menghantam mobil yang ditumpangi Dini dan merenggut jiwanya.
Di hari-hari akhir hidupnya masih beraktifitas dan penuh semangat. Berkebun dan menulis, adalah dua hal yang tak bisa lepas dari kehidupan sehari-harinya. Seminggu sebelum ajal menjemput, beliau bahkan masih mengunjungi putrinya, Marie Claire Lintang, yang kebetulan saat ini bertugas di Bandung. Putri cantiknya dari pernikahannya dengan Yves Coffin ini sebelumnya tinggal di Kanada. Sementara, anak laki-lakinya, Pierre Louis Padang, yang kondang sebagai sutradara film Hollywood ‘Minions’ dan ‘ Despicable Me’ tidak dapat datang karena jarak dan keterbatasan waktu.
Duduk di antara pelayat, menunggu kehadiran Lintang tiba ke pemakaman ibunya, saya merenung. Mencoba mengulang balik semua yang saya ketahui tentang NH Dini. Saya pernah mengunjungi rumah baca beliau yang dibangun di samping rumahnya, di Ngaliyan, Semarang. Kami sempat berbincang singkat. Memakai daster batik, dengan rambut digelung seadanya, beliau tampak seperti ibu-ibu biasa pada umumnya. ”Saya sedang menunggu Pierre, anakku,” katanya ramah. ”Dia tak mau minum teh bila tidak ditutup. Dia takut lalat!” sambungnya.
Siapa sangka, wanita di depan saya waktu itu, adalah master dari karya karya tulisan yang indah. Satu hal yang jelas, beliau memang berbeda. Beliau perempuan berprinsip kokoh dan free spirited. Tak seperti umumnya penulis perempuan yang karya tulisnya didominasi oleh ratapan dan keteraniayaan, Dini menawarkan ketangguhan perempuan. Di novel ‘Pada Sebuah Kapal’, ia tak segan berkisah tentang tokoh Sri yang tertaut hatinya pada kapten kapal tampan yang ia temui ketika berpesiar dengan anaknya yang masih balita.
Sri merasa pernikahannya menyesakkan, dan si kapten kapal adalah angin sejuk dari kepengapan hidupnya. Mereka bahkan memadu asmara di tengah samudra, meskipun si kapten sendiri adalah pria berkeluarga. Dini dengan dalam menorehkan proses percumbuan mereka dengan kiasan yang indah, dan perselingkuhan itupun berubah menjadi anggun.

Tentunya hal itu sangat tabu pada waktu itu. Tak pelak, pada masanya, ada pengamat sastra yang sampai mencap Dini “amoral”. Perempuan berkacamata ini menanggapinya dengan tanpa beban, “Ya, silakan saja punya pendapat gimana” ujarnya.
Namun, kritik itu akhirnya menjadi kerikil di tengah hamparan karya indahnya. Tak akan lekang dari benak saya, bagaimana manis nya NH Dini bertutur tentang kota Semarang dalam novel novel nya. Bahkan judulnya saja sudah menawarkan keindahan tersendiri: “Sebuah Lorong di Kotaku”, ” Langit dan Bumi Sahabat Kami”, “Padang Ilalang Belakang Rumah ku” dan lainnya. Judul-judul yang sederhana namun memikat.
Sekitar jam 10 pagi, Marie Claire Lintang tiba. Memakai kacamata hitam, ia terlihat terisak sejak memasuki ruangan. Di belakang Lintang, tampak seorang perempuan paruh baya berwajah cantik. Ia adalah Ayu Bulan Trisna. Seorang dokter dan maestro tari yang adalah sahabat lama NH Dini. Begitu eratnya persahabatan mereka, hingga Dini menulis nama Bulan Trisna di halaman depan novel ‘Pada Sebuah Kapal’.
Tak lama kemudian, jenazah diberangkatkan ke kota Ambarawa untuk dikremasi. Pertanyaan pun timbul dari berbagai pihak, mengingat prosesi Islam yang dilakukan sebelumnya. Islam tidak mengenal kremasi. Namun, hal itu tidak membuat saya heran, mengingat cara berpikir almarhumah yang bebas lepas nyaris tanpa batas.
Selain beberapa karangan bunga dari beberapa teman sesama seniman, tampak pula karangan bunga dari gubernur Jawa tengah dan Walikota Semarang. Selebihnya hanya puluhan pelayat yang mengantarkan kepergian sastrawati besar ini. Mungkin inilah wujud dari kurangnya perhatian dan apresiasi khalayak negeri ini pada pekerja seni.
Kepergian NH Dini, hanya seperti kematian kecil di sebuah sudut di kota Semarang pagi itu. Meskipun sesungguhnya kepergian nya adalah sebuah kehilangan besar bagi Indonesia. (Intan Rahadyanti – Penggemar seni & budaya)

