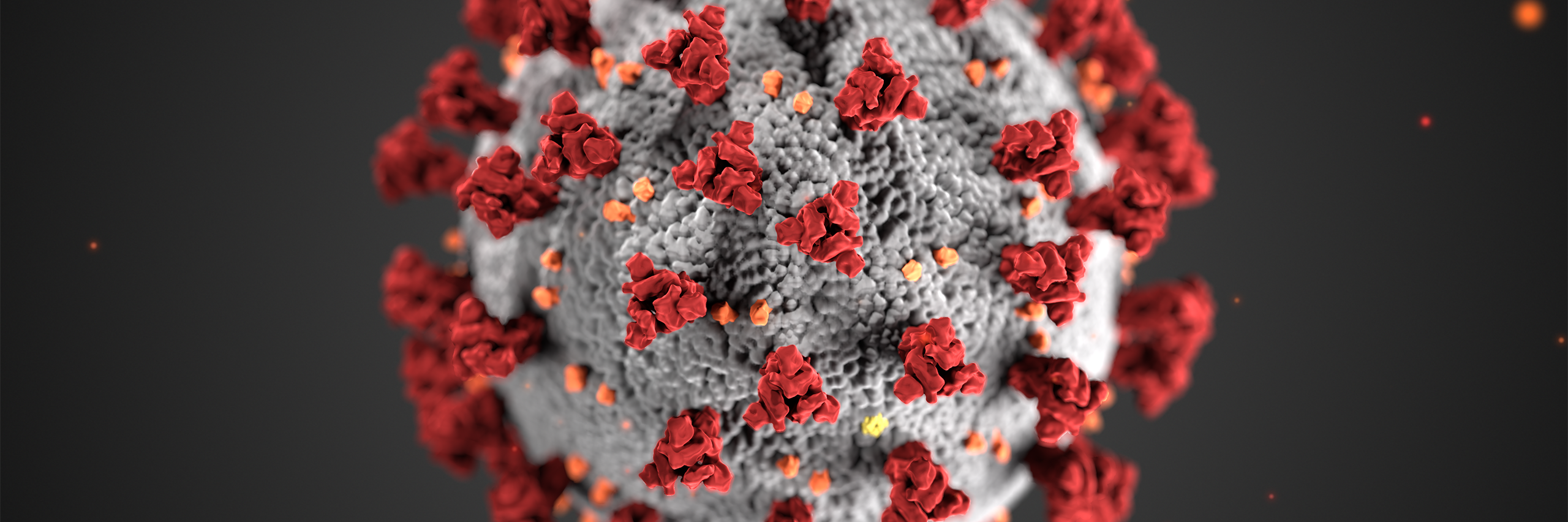Oleh: Mohamad Irfan
Sejak wabah virus corona merebak di Wuhan Tiongkok dan menyebar ke berbagai belahan dunia, kita seringkali mendengar atau membaca berita-berita, komentar-komentar atau pernyataaan banyak politisi, pemimpin dan pejabat negara memakai metafora perang atau kata-kata yang berkonotasi perang untuk menjelaskan tantangan yang kita hadapi.
Donald Trump, Presiden Amerika Serikat menggambarkan dirinya sebagai presiden masa perang, berperang melawan musuh yang tak terlihat. Di dalam pidatonya 5 April yang lalu, Ratu Elizabeth II dari Britania Raya kembali membangkitkan sebuah lagu Perang Dunia II. Begitu pula Perdana Menteri Italia, Giuseppe Conte juga demikian membangkitkan suasana perang dunia ke II di dalam upaya negaranya menanggulangi wabah pandemi covid 19 ini.
Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Gutierrez dalam kata sambutannya dalam KTT virtual G20 mengatakan: “We are at war with a virus . And This war needs a war-time plan to fight it.”
Rodrigo Duterte, Presiden Filipina dalam keterangan Persnya terkait kebijakan lockdown yang dia terapkan, “ Kita berperang melawan musuh yang ganas dan tidak terlihat. Dalam Perang yang luar biasa ini, kita semua adalah prajurit.

Di Indonesia, Presiden Jokowi juga mendeklarasikan hal yang sama dalam pidatonya atau instruksinya kepada jajaran di bawahnya dengan bahasa yang sama yaitu Perang melawan virus corona.
Nah, Dari semua pidato-pidato, komentar-komentar dan percakapan-percakapan seputar pandemi tersebut kita mendapatkan metafor-metafor yang berkonotasi perang yang sering kita dengar dan kita baca baik yang eksplisit seperti “Kita sedang Perang,” maupun yang implisit seperti “ musuh tak terlihat, ancaman, garis depan, pertempuran, dan sebagainya.
Perumpamaan seperti sedang perang ini terlalu memaksakan, Di dalam perang harus ada musuh (yaitu virus), pejuang-pejuang garis depan (yaitu tenaga medis), garis belakang (orang-orang yang mengisolasikan diri di rumah), pengkhianat yaitu orang-orang yang melanggar aturan social/physical distancing. Bahkan bahasa biomedis dan epidemilogi juga sudah dimilterisasi seperti “Kami ‘memerangi’ virus” dan “Tubuh kita memiliki mekanisme ‘pertahanan’ melawan patogen yang ‘menginvasi’ nya.
Memang metafor perang ini sangat menarik sebagai sebuah alat retorika politik, namun ia menyembunyikan perangkap, di dalam kasus pandemi Covid 19, bisa berbahaya.
Perang adalah bisnis negara. Beberapa orang berargumen peranglah yang sesungguhnya membentuk negara moderen. Penggiringan respon terhadap COVID 19 di dalam bahasa militer akan memperkuat pemikiran statis semacam itu. Ia akan memperkuat negara dan kekuasaannya.
Adalah benar adanya bahwa tatanan politik yang berlangsung saat krisis menghantam, negara memegang banyak kapasitas organisasional dan kekuasaan. Ia memiliki sebuah peranan krusial untuk berperan dalam menangani keadaat darurat pada saat belakangan ini. Namun ini bukan cuma menjadai masalah negara saja, namun juga menjadi masalah entitas-entitas politik lainnya juga, dari jaringan-jaringan spontan bottom-up, dari organisasi-organisasi tingkat kota sampat tingkat regional, bahkan sampai internasional seperti WHO. Metafora-metafora berkonotasi militer pada akhirnya membungkus kontribusi-kontribusi mereka dalam istilah-istilah militer.
Krisis ini bukan melulu soal medis kedokteran, pekerja kesehatan dan masyarakat manusia di seantero dunia, tapi juga soal-soal seputar kelas-kelas sosial-ekonomi, seperti para pekerja pasar swalayan, pekerja pengiriman barang dan pabrik-pabrik perlengkapan yang esensial, di semua negara yang menderita akibat virus. Melihat kepada kelas-kelas sosial-ekonomi lintas batas juga bisa membuat lebih banyak diskusi-diskusi mengenai kelompok masyarakat tunawisma, tempat-tempat pengungsi, syarat-syarat kerjadan perawatan kesehatan universal. Dan daripada memperkuat pemikiran statis militer, lebih banyak faedah menjelaskannya dengan misalnya istilah-istilah marxis, feminis, anarkis, atau liberal internasionalis.
Ya, penggunaan metafora perang melahirkan kategorisasi-kategorisasi secara diam-diam, misalnya di dalam suatu perang kita tak lagi warga negara, kita sekarang adalah “tentara”. Para politisi menuntut kepatuhan dan patriotisme ketimbang kesadaran dan solidaritas.
Secara tersamar kita telah melihat kategorisasi-kategorisasi ini, di hampir seantero dunia, banyak negara berubah cenderung menjadi otoriter yang berbahaya, seperti di Hongaria, dimana Perdana Menteri Viktor Orban meraih kekuasaan dalam keadaaan darurat dan peraturan-perundangan dengan keputusannya.
Hal yang sama terjadi di Filipina, Presiden Rodrigo Duterter, di dalam konteks UU Darurat Nasional, meraih hak untuk menghukum orang-orang yang menyebarkan “informasi palsu” mengenai pandemi, sebuah hak yang dapat dengan mudah digunakan untuk meredam perbedaan pendapat politik.
Di Kerajaan Inggris Raya, negara dengan instittusi-institusi demokratis yang kuat, RUU Virus Corona memberikan pemerintah kekuasaan untuk menahan dan mengisolasi orang, melarang pertemuan-pertemuan atau rapat-rapat umum termasuk protes-protes dan menutup pelabuhan-pelabuhan dan bandara-bandara. Menteri Kesehatan Inggris Raya pun dengan keras mengatakan: “We will fight this virus eith everything we have. We are in a war against an invisible killer and we have to do everything we can to stop it.”
Lagi pula, mendefinisikan pandemi sebagai perang tak terelakan melahirkan kebutuhan untuk mengidentifikasi musuh. Musuh disini adalah virus corona, namun banyak politisi telah menambahkan kualifiaksi-kualifikasi yang lain terhadap virus si musuh, misalnya pernyataan “China Virus” yang dilontarkan oleh Presiden Trump dan para pembuat kebijakan Amerika lainnya, telah mengobarkan semangat rasisme terhadap orang Asia di Amerika Utara.
Di Indonesia, pemerintah mengeluarkan perppu Nomor 1 Tahun 2000 yang memberikan pemerintah memiliki kekuasaan untuk menetapkan status PSBB atau Pembatasan Sosial Berskala Besar dimana pemerintah memiliki kekuasaan yang menahan dan mengisolasi orang, melarang pertemuan-pertemuan atau rapat-rapat umum termasuk unjuk rasa.
Di dalam Perppu ini, selain memberikan kekuasaan yang besar kepada pemerintah juga memberikan imunitas bagi pejabat negara pelaksana Perppu dan juga memberikan kekebalan hukum kepada pejabat negara yang mengambil segala tindakan berdasarkan Perppu bukan lah obyek gugatan yang bisa diajuikan ke pengadilan. Dengan demikian pejabat negara tidak bisa dituntut dan dipidana. Ketentuan-ketentuan tersebut menjadiakn penguasa atau pejabat negara bisa menyalahgunakan kekuasaan selama masa darurat pandemi, cenderung menjadi otoriter, tidak demokratis.
PSBB atau keadaan darurat pandemi virus corona kemudian oleh negara dijadikan alat untuk meredam suara-suara kritis yang mencari keadilan, misalnya pelarangan kaum buruh atau pekerja yang akan unjuk rasa mencari keadilan menolak RUU Cipta Kerja (RUU Omnibus Law), jika tetap melakukan unjuk rasa akan dibubarkan dengan paksa oleh Kepolisian. Dengan alasan keadaan darurat pandemi virus corona, kepolisian menangkap tiga aktifis kamisan yang merupakan mahasisa di malang. Mereka ditangkap dengan tuduhan penghasutan, padahal mereka hanya menyarakan ketidak adilan sosial di dalam masyarakat.
Kita juga masih melihat tindakan tutup paksa kios-kios, warung-warung kecil, penjaja makanan di pinggir-pinggir jalan, juga merupakan tindakan over reaksi atau semena-mena dengan alasan PSBB atau darurat pandemi virus corona. Karena kios-kios kecil, warung-warung kecil dan penjaja makanan di pinggir jalan sejak pandemi virus corona merebak, jumlah pembeli dan pengasilan mereka sudah menurun drastis, sepinya pembeli berarti yang datang ke toko atau warung mereka juga sehari juga kurang dari 10 orang, itupun tak datang sekaligus, tetapi paling tidak mereka masih bisa makan dari usaha mereka tersebut. Terus kalau mereka dipaksa tutup, habis sudah pendapatan mereka, lalu mereka makan apa. Sementara pemerintah tidak memberikan kompensasi apa-apa akibat hilangnya pendapatan mereka karena dipaksa tutup.
Bukan juga kebetulan, metafora perang semakin mendapat tempatnya dengan ditunjuknya perwira tinggi militer oleh Presiden Joko Widodo sebagaii Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 dan menteri kesehatan (yang menentukan diterima dan ditolaknya pengajuan PSBB oleh kepala daerah) juga dijabat perwira militer
Di sisi lain, selain negara yang cenderung menjadi otoriter semasa darurat pandemi virus corona ini, ada fenomena menarik yang menonjol yaitu makan menyebar luasnya jaringan organik yang berbasis gotong royong (mutual aid). Dari level jalanan sampai ke atas, dan seringkali dengan bantual media sosial, sejumlah besar orang-orang mengorganisisr jaringan solidaritas untuk saling membantu, terutama membantu orang-orang yang paling rentan.
Orang-orang bersatu dan mengorganisir diri bukan hanya di dalam lingkungan tetangga (di indonesia RT/RW), kampung-kampung, desa-desa, distrik-distrik, kota-kota, di kawasan-kawasan, tapi juga lintas negara, untuk saling membantu tanpa menyebutnya sebagai “perang” atau “tugas” militer. Bahasa gotong royong dan solidaritas malah jauh lebih bisa bekerja dengan baik dalam menghadapi dan mengatasi pandemi global ini.
Bahasa bisa membantu penggiringan narasi-narasi, interpretasi-interpretasi dan percakapan-percakapan tertentu dan pada saat yang sama menutup perspektif-perpektif alternatif. Ia memperkuat teori-teori tertentu mengenai bagaimana dunia bekerja dan mengesampingkan yang lain.
Penggiringan isu-isu politik di dalam bahasa perang selain menggambarkan kelaziman pemikiran militeris, ia juga memungkinkannya menjadi nyata. Semakin banyak dan sering kita menggunakan bahasa niliter, semakin membuat kita menganggap normal mobilisasi militer lalu semakin membuat kuat bercokolnya hirarki militer. Ketika krisis interasional berikutnya tiba, ketimbang membahas masalah-masalah struktural yang lebih dalam yang meyebabkannya, kita melompat kembali kepada narasi-narasi heroik mobilisasi militeris patriotis.
Siapa yang mendapatkan manfaat dari ini? Politisi-politisi dapat memproyeksikan suatu citra jendral-jendral desisif yang melindungi lahan/kapling mereka. Aparatur-aparatur koersif negara dapat memproyeksikan dirinya mereka sebagai pengemban tugas yang berbakti bukanya sebagai administrator dari amanat publik. Mereka kemudian dapat memobilisir citra ini untuk agenda politik mereka sendiri. Jika anda Trump, mungkin anda bisa menciptakan patriotisme anti China.
Apa yang hilang? Yang hilang adalah kesempatan untuk membangun sebuah pemahaman yang lebih bernuansa akan kemampuan-keampuan manusia yang tak dibatasi pada batas-batas nasional. Saat ini solidaritas internasional dan kemampuan-kemampuan umat manusia adalah yang kita butuhkan untuk menangani masalah-masalah berskala internasional lainnya, misalnya krisis iklim.
Ketika sebuah krisis global membangkitkan ekspresi-ekspresi murni gotong royong, imajinasi kita jadi sangat terbatas bila kita larut dalam penggiringan istilah-istilah yang statis dan patriotis. Alih-alih melihat seluruh kemanusiaan bangkit bersama-sama bergotong royong, imajinasi kita malah dibatasi di dalam bahasa militer.
Namun itu bukanlah cerita yang lengkap. Umat manusia akan keluar dari COVID dengan lebih bijaksana jika tidak membatasi pemahamannya atas respon terhadapnya dengan bahasa militer yang sempit.
Krisis pandemi virus corona adalah suatu tantangan internasional, tantangan seluruh umat manusia. Ia pastinya memerlukan mobilitas kolektif yang luar biasa, tetapi bukan untuk membunuh sesama manusia, dan bukan membuat orang tidak memanusiakan orang lain, dan bahasa-bahasa militeris tak diperlukan.
Mendorong ketahanan dan kebersamaan komunitas di dalam menghadapi kesulitan jauh lebih baik ketimbang membangkitkan mitos-mitos dan narasi-narasi heroik dan patriotik dan kampaye-kampanye militer. Ini sebuah jalan pintas kognitif untuk membangkitkan usaha kolektif, namun nararsi-narasi sempit yang direproduksi tersebut terbuka atau rentan akan eksploitasi oleh para politisi oportunistik.
Bila kita “sedang perang” untuk selama waktu yang tak bis ditentukan lamanya akan membuat kita lelah dan bisa menggagalkan semua upaya. Para pemimpin lebih baik menggalakkan tanggung jawab sipil dan solidaritas global ketimbang memakai metafora perang.
Bukan dengan cara menyuburkan citra serdadu bila pemerintah ingin meyakinkan orang untuk patuh terhadap otoritas kesehatan, namun dengan melibatkan warga negara, membangkitkan solidaritas dan penghormatan pada sesama manusia.
Perubahan dalam perspektif diperlukan, jika kita ingin mengatasi bukan hanya krisis ini, namun keadaaan-keadaan darurat global lainnya, termasuk perubahan iklim, penipisan lapisan ozone, pemanasan global, seperti yang WHO indikasikan, bertautan erat dengan penyebaran penyakit-penyakit menular.