Anak muda itu menulis dengan penuh gairah. Setiap pagi hingga sore ia kasak-kusuk, lobi kanan-kiri, mewawancarai tokoh-tokoh kenalannya, dan malam hari menulis untuk korannya. Apalagi sekarang dia mulai dipercaya menjadi salah satu petinggi di televisi swasta.
Hari-harinya amat produktif. Hampir setiap hari ada berita baru yang mengejutkan dan ucapan tokoh yang layak dikutip. Ada soal virus Corona yang mulai masuk Indonesia, ada Pemerintah Saudi yang menutup sementara kedatangan jemaah, dan lain-lain.
Menjadi wartawan di masa kini memang menggairahkan. Tak ada sensor. Siapa saja bisa bikin koran, tabloid, majalah, televiswi swasta, tanpa perlu takut dibredel pemerintah. Tak heran, si anak mudah itu berani mengkritik siapa saja yang mau dia serang dengan garang. Meledak-ledak. Bak koboi dengan dua pistol di tangan, ia menembak siapa saja yang mau ditembak. Rekan-rekan sepermainannya di kampung pun berdecak kagum.
Anehnya, orangtua si anak muda itu tak pernah sekali pun memuji –apalagi bangga– dengan apa yang dilakukan Si Anak Muda tersebut. Kenapa? Bukankah tulisannya lancar dibaca, berani, dan cukup produktif? Bukankah televisi swastanya konon banyak ditonton orang?

“Ah, dia tak lebih dari anjing penyerang bagi lawan-lawannya, sekaligus anjing kesayangan dari kelompoknya saja,” kata sang ayah suatu kali.
Kita tahu, selain “nyamuk”, wartawan juga mendapat julukan sebagai “anjing”. Dalam khasanah jurnalistik, kita kenal istilah “watchdog” alias anjing penjaga. Lalu, dalam buku Uncertain Guardians, Bartholomew Sparrow memakai istilah, watchdogs, attack dogs, dan lap dogs.
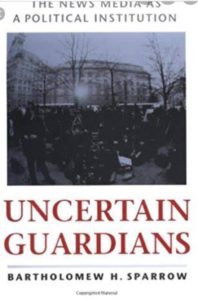
Rupanya, bagi sang ayah, anak muda itu tak lebih dari attack dog (anjing penyerang) bagi musuh-musuh kelompoknya, partai politiknya, kepercayaannya, atau ideologinya. Itu sebabnya ia selalu menyerang apa saja yang keluar dari kubu lawannya. Kalau perlu ucapan lawan dipelintir sedemikian rupa, atau dilihat dari sudut yang berbeda, sehingga layak untuk dihajar habis-habisan. Bagi anjing penyerang yang selalu menggonggong ini, membunuh adalah tujuan akhirnya.
Sebaliknya, pada saat yang sama, ia hanyalah lap dog (anjing piaraan yang penurut) bagi kawan-kawanya, nara sumber kesayangannya, partainya, atau ideologinya. Karena itu, hampir tak pernah terdengar kritik bagi rekan-rekannya. Apa yang dikatakan pimpinannya adalah kebenaran atau jadi arahan untuk menulis. Jika mereka bersalah, harus dicari pembenarannya. Atau, kalau perlu, disembunyikan agar tak terbaca oleh publik. Bagi anjing kecil yang penurut ini, kesenangan hati sang bos adalah cita-citanya.
“Ia telah mengecoh publik. Ia tak pernah berpikir apa akibat tulisannya bagi masyarakat banyak. Ia tidak berguna dalam pembangunan peradaban,” keluh sang ayah. Pendeknya, di mata sang ayah, apa yang dilakukan anak mudah itu tak lebih merupakan bagian dari “politik kotor” (dirty politics) atau malah political orgy (pesta cabul politik).

Lalu, apa sebenarnya yang diharapkan oleh sang ayah? “Tak jauh-jauh. Jadilah anjing penjaga (watchdog) masyarakat yang baik,” jawabnya. “Gonggong siapa saja yang menipu, bongkar semua yang palsu, tak peduli apakah itu termasuk ketua partaimu!”
Anak muda itu mungkin sempat merenung. Jangan-jangan ia lebih cocok jadi pengurus partai ketimbang jadi wartawan! (Kemala Atmojo)

