TAHUN 2020 yang belum lama berlalu dan menjadi salah satu periode terkelam umat manusia tersebab cengkeraman pandemi Covid-19 membuat produktivitas menurun. Akan tetapi hal itu tak terjadi pada Akmal Nasery Basral, novelis eklektik yang meluncurkan lima buku di tengah bisnis perbukuan nasional yang sedang anjlok akibat banyak toko buku tutup ditambah habit masyarakat yang belum terbiasa membaca format e-book.
Apa yang menyebabkan mantan jurnalis Gatra dan Tempo ini mampu mengatasi kondisi kurang kondusif itu? Didi Prambadi dari Indonesia Lantern mewawancarai penulis 19 buku ini melalui e-mail. Petikannya:
Bagaimana resepnya Anda bisa menulis banyak buku dalam suasana wabah yang sedang menjangkiti dunia?
Sebetulnya tak ada resep khusus. Saya hanya menerapkan pesan Ernest Hemingway “Just type and bleed”. Kalau dilihat dari rentang waktu novel saya pertama kali terbit (Imperia, 2005) sampai akhir tahun lalu saya sudah berkiprah selama 15 tahun. Selama 14 tahun (2005-2019) saya hanya menghasilkan 15 buku. Jadi produktifitas yang biasa-biasa saja. Baru pada 2020 saya menghasilkan empat buku karya sendiri dan satu buku yang merupakan kumpulan tulisan 110 penulis Satupena Indonesia berjudul Kemanusiaan Pada Masa Wabah Corona (Balai Pustaka) dengan editor Dr. Nasir Tamara.
Empat buku lainnya apa saja? Apakah keempatnya dalam satu genre?
Tidak. Saya suka mengeksplorasi lintas genre. Empat buku saya tahun lalu ada yang bentuknya novel biografi (Setangkai Pena di Taman Pujangga, kisah tentang ulama dan pujangga fenomenal, Buya HAMKA, saat remaja sampai usia 30 tahun), ada novel drama (Dilarang Bercanda dengan Kenangan 2: Gitasmara Semesta), ada kumpulan cerpen berjudul Putik Safron di Sayap Izrail dan sebuah fiksi ilmiah berjudul Disorder. Tiga buku pertama diterbitkan Republika Penerbit yang membuat saya terpilih sebagai Penulis Produktif 2020 versi Republika. Ada pun novel Disorder yang termasuk subgenre pandemic-apocalyptic diterbitkan oleh Bentang Pustaka.
Pandemic-apocalyptic? Apakah mengenai Covid-19?
Bukan. Ini tentang pandemi di masa depan yang dipantik oleh keluarga virus H1N1 atau SOIV (Swine Origin Influenza Virus). Setting waktunya saya buat terjadi pada 2026.
Menarik. Bagaimana ide Disorder itu muncul?
Pada April 2020 terbit novel The End of October karya Lawrence Wright yang berkisah pandemi berikutnya akan datang dari Indonesia. Penyebabnya adalah virus Kongoli, yang merupakan nama fiktif. Namun perencanaan novel ini cukup lama, bahkan melibatkan sutradara kondang Ridley Scott dalam pematangan gagasannya. Novel itu ternyata juga sedang dibaca Salman Faridi, CEO Bentang Pustaka, yang memberikan tantangan kepada saya jika mampu menulis novel serupa sebelum Oktober 2020, maka karya saya itu akan diterbitkan pada akhir tahun. Maka pada 1 Juni saya mulai menulis dan selesai pada 25 September 2020, atau setelah 117 hari.
Apa perbedaan dalam mengerjakan novel Disorder dengan novel-novel Anda lainnya?
Setiap novel tantangannya berbeda. Untuk Disorder salah satu yang terberat. Karena saya tak memiliki latar belakang pendidikan dokter atau kesehatan masyarakat (public health), maka saya membuat sebuah cerita singkat dalam lima bab pendek yang saya konsultasikan kepada 4 (empat) orang pakar, yakni ahli epidemiologi klinis, ahli neuroscience, ahli biologi molekuler dan stem cell, dan seorang pakar sosiologi perkotaan.
Masukan mereka lalu saya kembangkan menjadi novel utuh 54 bab dan sebuah Epilog. Setelah naskah selesai lalu saya kirimkan kepada tujuh orang pembaca pertama (first readers) yang berbeda dengan empat ahli sebelumnya. Di antara para pembaca pertama adalah Prof. Effendi Gazali, Nezar Patria (mantan Pemred The Jakarta Post) dan Yudhistira ANM Massardi, sastrawan senior yang juga jurnalis kawakan.
Bagaimana dengan kisah penulisan novel lainnya? Apa saja yang berkesan?
Dwilogi Dilarang Bercanda dengan Kenangan punya kisah unik. Awalnya ini hanya sebuah cerpen berjudul sama yang terdapat dalam antologi Ada Seseorang di Kepalaku yang Bukan Aku (2006), kumpulan cerpen pertama saya. Cerpen itu saya kembangkan menjadi sebuah novel sekitar 500 halaman dan diterbitkan Republika Penerbit pada akhir 2018. Ternyata cukup banyak pembaca yang suka dan minta dilanjutkan kisahnya. Akhirnya saya buat sekuelnya Dilarang Bercanda dengan Kenangan 2: Gitasmara Semesta yang terbit pada Agustus 2020.
Judul Dilarang Bercanda dengan Kenangan ini terasa romantis sekaligus tragis. Apa inti kisahnya?
Novel ini tentang seorang pemuda Indonesia yang sedang kuliah di Leeds, Inggris, pada 1997. Baru sebulan dia di sana terjadi kematian Putri Diana Spencer. Sang pemuda menyempatkan diri datang ke London untuk melihat pemakaman kolosal yang menarik minat jutaan orang untuk datang juga ke ibu kota Inggris itu. Di sana, tanpa terduga dia bertemu dengan cinta pertamanya saat di Indonesia, dan bertemu juga dengan seorang jurnalis perempuan berdarah blasteran Rumania-Kurdi. Dalam beberapa hari di London itu, perasaan sang mahasiswa Indonesia seperti bandul yang bergerak ke kanan dan ke kiri untuk mencari cinta sejati.
Namun ini bukan kisah cinta biasa karena pada latar belakangnya diceritakan juga krisis moneter (krismon) ’97 dan Reformasi Mei ’98 yang terjadi di Indonesia sampai tsunami Aceh 2004. Jadi memang ada unsur romansa sekaligus tragedi dalam kisah ini yang berkelindan.
Saya dengar novel Anda ada yang sedang diterjemahkan ke dalam Bahasa Jepang?
Betul. Itu novel Te o Toriatte (Genggam Cinta) yang diterbitkan Gramedia Pustaka Utama pada akhir 2019, saat ini sedang diterjemahkan ke dalam Bahasa Jepang oleh seorang jurnalis Kyodo News Service. Semoga bisa terbit tahun ini.
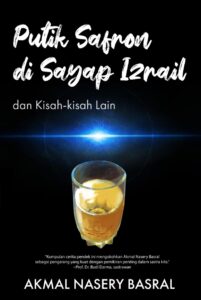
Judul novel Anda sudah dalam bahasa Jepang? Kisahnya tentang apa?
Ini ada kisah uniknya juga. Sebetulnya novel Te o Toriatte (Genggam Cinta) ini juga berasal dari cerpen–seperti Dilarang Bercanda dengan Kenangan—hanya saja cerpen aslinya dalam Bahasa Inggris berjudul “Swans of the Rising Sun” pada antologi Project Sunshine for Japan (2013) yang diterbitkan dalam rangka Peringatan Dua Tahun Triple Disaster Tohoku-Fukushima. Antologi itu merupakan proyek solidaritas internasional 40-an penulis dari 15 negara yang digagas Mansoureh Rahnama dari Universitas Dortmund, Jerman. Saya diminta mewakili penulis Indonesia.
Sedangkan dari Jerman antara lain ada Guenter Grass, penerima Nobel Sastra 1999. Setelah lima tahun cerpen saya itu hanya beredar di kalangan pembaca luar negeri, pada akhir 2018 saya dan Gramedia Pustaka Utama sepakat mengembangkan kisah cerpen itu menjadi novel dalam Bahasa Indonesia. Saya mengganti judulnya dari “Swans of The Rising Sun” menjadi “Te o Toriatte” yang secara harfiah berarti “marilah kita bergenggaman tangan.”
Judul ini saya pilih karena kisah ini menautkan dua bencana alam besar, yakni tsunami Aceh (2004) dan triple disaster Jepang (2011) melalui kisah seorang penyintas remaja putri bernama Meutia yang setelah orang tua kandung dan ketiga adiknya tewas dalam tsunami, pasutri di Fukushima yang membaca kisahnya di media massa lalu mengadopsinya sebagai anak angkat mereka.

Namun kemudian setelah Meutia pindah ke Jepang, bencana alam terjadi lagi dalam hidupnya dan menewaskan orang tua angkatnya. Akibatnya, Meutia mengalami PTSD (Post-Trauma Stress Disorder) yang serius di dalam usahanya untuk mencapai cita-cita sebagai ahli komputer. Novel ini sudah diulas oleh Yahoo! Japan pada Maret 2020 dan dua bulan kemudian ditulis oleh koran Asahi Shimbun, harian terbesar kedua di Jepang bertiras sekitar 6 juta eksemplar per hari. Semoga dengan adanya terjemahan Bahasa Jepang dari novel ini akan semakin banyak pembaca Jepang yang tahu Sastra Indonesia kontemporer.
Karya apa lagi yang akan muncul dalam waktu dekat?
Saya diajak Dr. Murti Bunanta, pendiri dan ketua Kelompok Pencinta Bacaan Anak (KPBA) untuk berpartisipasi dalam antologi cerpen anak. Ini pertama kalinya saya menulis cerpen anak meski sudah menulis dua novel anak dan remaja yakni Batas: Antara Keinginan dan Kenyataan (2011) yang berlokasi di Entikong, Kalimantan Barat, dan Anak Sejuta Bintang (2012) yang berlokasi di Jakarta tahun 1950-an.
Pada antologi KPBA ini selain ada Bu Murti dan saya, juga diikuti beberapa penulis lain seperti Alberthiene Endah atau Iksaka Banu, penerima penghargaan Kusala Sastra Khatulistiwa (Khatulistiwa Literary Award) 2014. Saat ini tinggal proses cetak. Setelah itu tahun ini saya merencanakan menerbitkan beberapa novel lagi dan biografi dari seorang chef Indonesia yang menghabiskan masa kanak-kanak dan remaja di Eropa, sebelum berkiprah di Indonesia dan menjadi salah seorang master chef paling disegani saat ini.
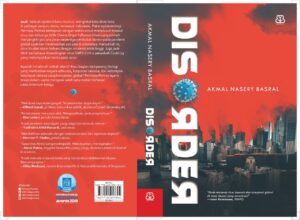
Siapa saja penulis atau sastrawan yang menginspirasi Anda?
Banyak. Seiring perjalanan waktu dan perkembangan wawasan, pelbagai sastrawan dengan beragam penulisan yang saya baca ikut membentuk minat dan gaya penulisan saya sendiri. Ketika masih SMA, novel sastra serius yang pertama kali saya baca adalah Doktor Zhivago (Boris Pasternak) selain beberapa roman Balai Pustaka yang dijadikan materi ajar di sekolah.
Setelah itu saya tertarik membaca karya-karya Yukio Mishima, Yasunari Kawabata, Romo Mangunwijaya, Ahmad Tohari, Kuntowijoyo, Ernest Hemingway, Tahar Ben Jelloun, Mustafa Luthfi Al-Manfaluthi, Marguerite Duras, Chinua Achebe, Ben Okri, Jose Saramago, Pearl S. Buck, Gabriel Garcia Marquez, Paulo Coelho, Haruki Murakami, Eka Kurniawan, Arafat Nur, Dewi “Dee” Lestari, Jonathan Safran Foer, dan lain-lain.
Anda pernah menjadi wartawan majalah berita. Apakah pengalaman sebagai jurnalis itu ikut memudahkan metamorfosis menjadi penulis?
Ya, sangat membantu saya. Ketika saya baru 3-4 bulan bekerja di Tempo, majalah itu dibredel karena Laporan Utama pembelian kapal laut dari Jerman Timur (Juni 1994). Setelah itu saya ikut rombongan yang pindah (mendirikan) majalah Gatra. Saya mulai dari awal lagi dan belajar menulis berita dari banyak senior seperti Mas Didi Prambadi sendiri yang saat itu menjadi Redaktur Pelaksana Kompartemen Luar Negeri (Internasional) atau Mas Yudhistira Massardhi, Redaktur Pelaksana Kompartemen Seni Budaya yang juga seorang penyair.

Itu periode yang mengokohkan fondasi saya sebagai seorang reporter yang melakukan observasi lapangan, menjalankan wawancara, dan menuangkannya ke dalam tulisan. Setelah dari Gatra saya sempat ke Gamma lalu kembali ke Tempo sampai 2010. Setelah itu saya memutuskan pindah kuadran menjadi penulis penuh waktu dengan konsentrasi utama sebagai novelis, meski sesekali menulis kolom dan esei (non-fiksi), sampai sekarang.
Bagaimana caranya jika pembaca Indonesia Lantern ingin membaca karya-karya Anda? Bisa didapatkan di mana?
Hampir seluruh karya saya bisa didapatkan di Amazon.com. Untuk versi digital bisa diunduh dari Google Play, kecuali Disorder yang baru terbit mungkin baru tersedia versi digitalnya pada bulan Maret 2021.


Wonderful items from you, man. I’ve have in mind your stuff previous to and you’re just too excellent.
I really like what you’ve got right here, certainly like what you’re saying
and the way through which you assert it. You’re making it enjoyable and you continue to
care for to keep it wise. I cant wait to learn much more from you.
This is actually a wonderful site.
Howdy! I know this is kinda off topic however I’d figured
I’d ask. Would you be interested in trading links or maybe guest writing a blog post or vice-versa?
My website discusses a lot of the same subjects as yours
and I feel we could greatly benefit from each other. If you are interested feel
free to shoot me an email. I look forward to hearing from
you! Superb blog by the way!
Pretty great post. I just stumbled upon your weblog and wanted to say
that I’ve really loved surfing around your blog posts.
In any case I will be subscribing on your rss feed and I hope you write once more very soon!
We absolutely love your blog and find nearly all of your post’s
to be what precisely I’m looking for. can you offer guest writers to write content in your case?
I wouldn’t mind writing a post or elaborating on many of the subjects you write regarding here.
Again, awesome site!
My brother recommended I would possibly like this blog. He was once entirely
right. This put up actually made my day. You cann’t consider simply how much time
I had spent for this info! Thank you!
I’ll immediately clutch your rss as I can not to find your e-mail
subscription hyperlink or e-newsletter service.
Do you’ve any? Kindly permit me recognize so that I may just subscribe.
Thanks.
My spouse and I absolutely love your blog and find nearly
all of your post’s to be exactly what I’m looking for.
Would you offer guest writers to write content available for you?
I wouldn’t mind producing a post or elaborating on a few of the subjects you write related to here.
Again, awesome web log!
Excellent article. Keep posting such kind of information on your page.
Im really impressed by your site.
Hey there, You have done an incredible job.
I will definitely digg it and in my opinion recommend to my friends.
I’m confident they’ll be benefited from this website.
This is very interesting, You’re a very skilled blogger.
I have joined your rss feed and look forward to seeking
more of your magnificent post. Also, I’ve shared your website in my social networks!
Hi, Neat post. There is an issue with your site in web explorer, may check this?
IE still is the market chief and a huge section of people will omit your wonderful writing due to this problem.
Ridiculous story there. What happened after? Take care!